
Suara.com - Bagi para penentang Orde Baru, neraka memiliki dua alamat. Pertama, penjara resmi seperti Cipinang, tempat sisa-sisa hidup para terbuang dikumpulkan. Kedua, ruang-ruang gelap tak bernama seperti “Kremlin”, tempat tubuh disiksa dan identitas dilenyapkan dalam sunyi.
JAKARTA tidak pernah benar-benar senyap. Subuh ataupun larut malam, selalu ada kebisingan. Tapi untuk Wilson Obrigados, eks aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), ada alamat-alamat yang menyimpan sunyi lebih pekat dari malam itu sendiri.
Jalan Kramat V salah satunya. Dari luar, ia hanya barisan rumah tua yang lelah, catnya mengelupas dimakan cuaca dan abai. Tak ada plang nama, tidak ada penanda sejarah.
Namun, bagi mereka yang pernah melewatinya dengan mata terpejam dan jantung berdebar di dalam mobil tanpa pelat, alamat itu adalah koordinat neraka. Bisikan di antara para aktivis menyebutnya: ‘Kremlin’—akronim Kramat Lima.
Kremlin bukanlah sekadar nama. Ia adalah prosedur—proses penghilangan. Seseorang dibawa masuk, dan dunia luar berhenti ada.
Hukum formal, dengan pasal-pasal dan pengacaranya, menguap di ambang pintunya. Yang tersisa hanyalah otoritas absolut dari para interogator dan gema jeritan yang tak akan pernah sampai ke telinga jalanan yang ramai.
Bagi Wilson, sejarawan yang tubuhnya adalah arsip dari perlawanan terhadap otoritarian Orba itu sendiri, Jakarta adalah sebuah geografi ketakutan.
“Yang paling menyeramkan adalah Kramat Lima,” ia memulai, suaranya tenang, seolah sedang membedah peta lama, “dan Markas BIA di Ragunan. Keduanya jadi pusat teror.”
![Wilson Obrigados, mantan aktivis PRD yang pernah menjadi tahanan politik (tapol) di Lapas Cipinang semasa rezim Orde Baru, dan kini menjadi sejarawan. [dokumentasi/Wilson]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/30/70862-wilson-obrigados-tapol-sejarawan.jpg)
Di sana, penangkapan adalah penculikan. Intel-intel berpakaian sipil datang seperti bayangan, menarikmu dari keramaian atau keheningan kamarmu.
Tak ada surat penangkapan, tak ada penjelasan. Kata dia “kau hanya lenyap”, dan di balik dinding-dinding itu, penyiksaan dan intimidasi menjadi satu-satunya bahasa.
Ironis, kompleks rumah nomor 14, 16, dan 17 itu pernah menjadi nadi pergerakan buruh terbesar di Indonesia dan berhaluan demokrasi rakyat: kantor Dewan Nasional Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
Sejarah seolah gemar membalik nasib. Setelah prahara 1965, bangunan itu diambil alih tentara, disulap menjadi markas unit Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksus Kopkamtib).
Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (1986:250) menyebut Kopkamtib terbentuk atas kompromi antara Soekarno dan Soeharto.
Saat G30S meletus dan terbunuhnya Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Soekarno meminta Soeharto yang masih berpangkat Mayor Jenderal mengisi kekosongan pucuk pemimpin TNI AD.
Soeharto bersedia, dengan syarat diserahkan tugas melakukan ‘pemulihan keamanan dan ketertiban’ yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kopkamtib.
Lembar sejarah kemudian mencatat, fungsi Kopkamtib meluas dan melebihi tujuan semula, menangkapi para pengikut dan orang-orang yang diasosiasikan dengan PKI maupun orang-orang pengkritik Orba.
Era 90an, di Kremlin, tembok-temboknya adalah saksi bisu. Saksi dari tubuh-tubuh yang dipaksa membocorkan rahasia perlawanan, dari semangat yang coba dipatahkan sebelum sempat diadili.
Hantu-hantu di Cipinang
JIKA Kremlin adalah ruang hampa hukum, maka Lembaga Pemasyarakatan Cipinang adalah ekosistem lain.
Lapas di timur Jakarta itu menjadi “republik” bagi mereka yang terkutuk, sebuah titik temu yang aneh bagi para penentang rezim dari segala spektrum.
Di balik jerujinya, udara terasa lebih padat oleh sejarah.
![Tim sepakbola tahanan politik Lapas Cipinang yang dipimpin Kolonel Abdul Latief selaku manajer dan Xanana Gusmao sebagai kapten kesebelasan. [Dokumentasi/Wilson]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/30/91168-tim-sepakbola-tapol-xanana-gusmao-di-lapas-cipinang.jpg)
Sejak 1980-an, Cipinang telah menjadi rumah bagi tapol korban ’65, aktivis Islam, pejuang kemerdekaan dari tanah yang jauh (Timor Lorosae dan Papua), dan akhirnya, gelombang anak-anak muda pemberang dari era 90-an.
Wilson dan kawan-kawannya dari PRD dilempar ke dalam kuali ini pada medio sembilanpuluhan.
Mereka mendarat di Blok II D, sudut penjara dengan udaranya sendiri, yang lebih dikenal sebagai Blok Eki—Ekstrem Kiri.
Di sanalah mereka bertemu para ‘hantu’. Lelaki-lelaki tua yang telah dikubur hidup-hidup oleh negara, dituduh PKI, dan telah menghabiskan puluhan tahun menatap vonis mati yang bisa datang kapan saja.
Persahabatan terjalin di tempat paling mustahil, di antara dua generasi berlawan yang dipisahkan oleh waktu namun disatukan oleh nasib.
Wilson mengingat Kolonel Abdul Latief, tokoh penting pada peristiwa Gestok 65. Di selnya yang sesak, sang kolonel menyimpan sebuah kardus usang.
Isinya bukan harta, melainkan koleksi foto-foto lusuh para tapol PKI, kawan-kawan seperjuangannya. Banyak dari foto itu telah diberi tanda silang.
“Tanda silang ini kenapa bung?” tanya Wilson.
"Setiap kali ada napol PKI yang dihukum mati atau meninggal dunia di Cipinang sini, saya beri tanda silang di foto mereka.”
Mata Wilson tertumbuk pada tiga foto tapol 65 lainnya, yakni Asep Suryaman, Bungkus, dan Marsudi.
Ketiga foto itu juga diberi tanda silang, padahal mereka masih bernapas di blok yang sama.
“Mereka ini masih ada bung, di sini.”
Latief tersenyum getir.
"Harusnya mereka sudah mati, tapi tidak jadi dieksekusi karena dapat tekanan dari dunia internasional."
Lalu, dengan seloroh, ia menambahkan, "Saya berkawan dengan hantu."
Di balik tawa getir Latief dan bayang-bayang vonis mati para tahanan PKI, kehidupan menolak untuk menyerah pada ajal.
Asep Suryaman—ketika itu sudah berusia 70an tahun—adalah mantan anggota Biro Khusus PKI dan kepala Departemen Pendidikan Sekretariat PKI. Dia seorang pemikir tulen.
Setelah Gestok, ia bersama sisa kader PKI menempuh jalan Maois, membangun basis gerilya di Blitar. Tatkala Soeharto melancarkan “Operasi Trisula”, Asep melarikan diri ke Jawa Barat. Ia ditangkap di sana pada bulan September 1971, saat bekerja di Bandung sebagai pedagang kain perca.
“Semasa di penjara, Asep justru jadi Ketua Persatuan Badminton Narapidana Cipinang,” kata Wilson.
Bungkus, juga berusia 70an tahun, adalah mantan sersan Cakrabirawa pengawal Soekarno. Dia ditangkap pada 8 Oktober 1965.
“Di sel, dia sibuk membuka usaha menjahit.”
Sementara Marsudi, baru berumur 60an, adalah mantan sersan mayor AURI. Dia ditangkap karena dituduh membunuh empat jenderal Angkatan Darat.
“Marsudi menemukan ketenangan di gereja.”
Namun, penderitaan adalah penghuni tetap. Wilson menyaksikan Sukatno, anggota CC PKI, yang tubuhnya telah digerogoti stroke hingga tak berdaya.
Sukatno, mantan ketua organisasi massa Pemuda Rakyat—satu-satunya ormas yang diakui PKI sebagai organisasi sayap partai dalam statutanya. Berlatar belakang teknisi listrik, dia merupakan pejuang kemerdekaan dan terpilih menjadi anggota parlemen tahun 1955.
"Badannya kurus kering seperti kulit membalut tulang," kata Wilson.
Kalimat itu melucuti semua ideologi, menyisakan potret manusia yang rapuh. Sukatno meninggal saat Hari Raya Idul Adha 1997, di RS Polri, jauh dari kawan-kawannya.
“Itu adalah terakhir kalinya kami menemuinya di dalam penjara,” kenang Wilson.
Kematiannya adalah titik akhir dari kemanusiaan yang dibiarkan membusuk oleh rezim.
![Tapol PRD bersama narapidana di Blok III E Lapas Cipinang Tahun 1997, Jakarta.Wilson berdiri buka baju dibelakang kedua dari kiri. [Dok Pribadi Wilson]](https://media.suara.com/pictures/original/2025/09/28/14757-tapol-prd-bersama-narapidana-di-lapas-cipinang.jpg)
Impian Museum HAM
Teror tak pernah berhenti di pintu penjara. Ia merembes, mengalir ke dalam rumah, ke meja makan, ke masjid di ujung jalan.
Wilson mengenang ibunya, seorang perempuan berhijab yang harus menanggung stigma "PRD Komunis" yang didengungkan dari mimbar masjid dekat rumah mereka.
“Ibu saya sampai marah. Tahun-tahun awal, ia tak mau salat di masjid dekat rumah, memilih masjid lain,” ucapnya.
Namun, kemanusiaan seringkali muncul dari tempat tak terduga. Para tetangga dan pengurus RT justru memberikan dukungan moral.
Stigma itu akhirnya luruh, terkikis oleh kesadaran warga atas kebobrokan rezim yang semakin telanjang, meskipun lagi-lagi, rekonsiliasi itu sunyi.
“Setelah reformasi 1998, masjid kembali normal, dan ibu saya kembali ke sana.”
Kini, dua dekade lebih setelah reformasi, Kremlin mungkin telah berganti rupa. Ragunan telah menjadi gedung lain. Waktu adalah penghapus yang efisien.
“Penjara adalah situs memorabilia dari sebuah rezim otoriter,” kata Wilson, nadanya tegas.
“Kesaksian para aktivis yang pernah ditahan dan disiksa di sana harus didokumentasikan.”
Ia lalu bercerita tentang kunjungannya ke Timor Leste, melihat bagaimana Penjara Comarca diubah menjadi museum HAM. Sebuah tempat untuk merawat luka, bukan untuk melupakannya.
“Saya punya mimpi,” ujarnya di akhir percakapan, “suatu hari nanti, penjara atau tempat penahanan di sini bisa jadi museum HAM.”

Ingatan kolektif masyarakat tentang tapol PKI dari balik jeruji penjara Orde Baru telah memudar, seiring perkembangan zaman. Jurnalis Suara.com mencoba menjalinnya kembali.

Apa makna pengibaran bendera setengah tiang dan satu tiang penuh?
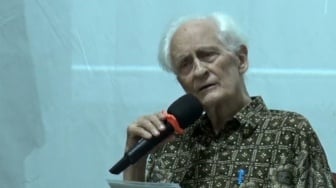
Romo Magnis Suseno melontarkan pertanyaan provokatif: "Andai kata Bung Karno melarang PKI pada 6 Oktober, apakah pembunuhan massal akan terjadi?".
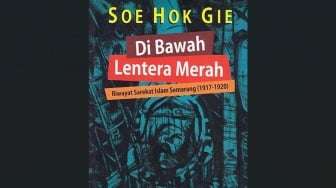
Media-media tersebut menjadi oposisi dari pers besar yang saat itu cenderung pragmatis dan membela kepentingan pemerintah kolonial Hindia-Belanda.

Salinan ijazah terlegalisir yang dipakai Calon Presiden di Pilpres 2014 dan 2019, tulis Bonatua
 nonfiksi
nonfiksi
Anak-anak, remaja, hingga dewasa ditangkap Polres Jakarta Utara atas tuduhan ikut aksi Agustus 2025. Banyak yang sebenarnya tidak ikut demonstrasi. Mereka dianiaya polisi.
 polemik
polemik
Jangan sebut mereka korban jika mereka berangkat secara sadar untuk menipu orang lain demi gaji dolar,
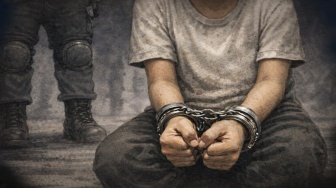 nonfiksi
nonfiksi
Polres Magelang Kota diduga melakukan asal tangkap terhadap banyak bocah setelah aksi Agustus 2025. Banyak di antara anak-anak itu mengaku disiksa selama dalam tahanan.
 polemik
polemik
Analisis dari akademisi Universitas Airlangga (Listiyono Santoso dkk) menyebutkan bahwa kultur patrimonial dalam birokrasi menjadi penghambat utama
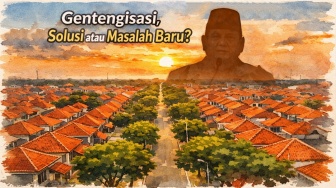 polemik
polemik
Gentengisasi, di satu sisi menjanjikan estetika dan ekonomi kerakyatan, di sisi lain terbentur masalah teknis, budaya, dan anggaran
 polemik
polemik
Pernyataan tegas Jokowi ini ditegaskan kala menanggapi isu Gibran disebut-sebut berpotensi besar jadi calon presiden (capres) 2029.