
Suara.com - PEGIAT hak asasi manusia dan demokrasi menilai upaya pemerintah untuk mengikis kebebasan berpendapat tak ada habis-habisnya. Masih hangat rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang salah satu pasalnya membatasi kebebasan pers, kini disiapkan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.
Salah satu materi revisi UU Polri ini adalah menambah kewenangan kepolisian mengawasi hingga memblokir ruang siber. Penambahan kewenangan itu tertuang dalam draf revisi UU Polri Nomor 2 Tahun 2002.
Revisi UU Polri ini telah disepakati sembilan fraksi DPR RI menjadi inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna pada Selasa, 28 Mei 2024. Selanjutnya akan dibahas di badan legislatif DPR RI.
Dalam draf revisi UU Polri yang diperoleh Suara.com, penambahan wewenang pembinaan, pengawasan dan pengamanan di ruang siber itu diatur dalam Pasal 14 huruf b. Kemudian Pasal 16 huruf q memberi wewenang melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan akses internet.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya mengatakan, penambahan kewenangan itu membuka peluang Polri melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Ada gelagat menciptakan otoritarianisme.
"Penambahan kewenangan yang diberikan dalam RUU Polri ini juga pasti akan memberikan satu efek lanjutan terkait dengan akses pembatasan kebebasan berpendapat dan beropini serta berekspresi yang ada di sosial media," kata Dimas kepada Suara.com, Senin (3/6/2024).
Peristiwa pemutusan atau pelambatan jaringan internet di Indonesia bukan hal baru. Beberapa kasus menunjukkan pembatasan internet dilakukan saat warga mengkritik dan melawan kebijakan pemerintah. Salah satu kasusnya, penolakan warga atas penambangan batu andesit di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada awal Februari 2022 silam.
Saat konflik semakin memanas antara warga dengan aparat kepolisian, jaringan internet ketika itu diputus. Selain itu akun-akun media sosial yang vokal menyuarakan perlawanan masyarakat Wadas juga diretas atau diambil alih. Sejumlah aktivis yang mengadvokasi warga Wadas menduga hal itu sengaja dilakukan untuk menutup akses informasi atas konflik antara warga dengan negara.
Kasus lainnya, yakni pemutusan dan pelambatan layanan internet di Papua dan Papua Barat yang berlangsung selama pertengahan Agustus hingga September 2019. Pelambatan jaringan internet terjadi di tengah isu rasisme yang dialami pelajar Papua di asrama mahasiswa Papua, di Surabaya, Jawa Timur.
Pada saat itu pemerintah berdalih pemutusan dan pelambatan jaringan internet dilakukan demi mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks. Namun pemutusan itu berdampak terhadap kegiatan masyarakat yang membutuhkan jaringan internet, serta membuat masyarakat kesulitan mengakses informasi.
Belakangan peristiwa itu digugat koalisi masyarakat sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 2020. PTUN memutus Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika terbukti bersalah. Jokowi dan Kominfo dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
Dua peristiwa ini setidaknya dinilai sebagai contoh, bagaimana kewenangan pemutusan internet digunakan untuk mengekang kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan mengakses informasi. Dimas menegaskan, pemutusan dan pelambatan internet berpotensi melanggar hak asasi manusia atau HAM.
Sementara, berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet pada 2021 terjadi 12 kasus gangguan internet di Indonesia. Sebanyak 11 kasus terjadi di wilayah Papua. Dalam laporannya, SAFEnet menyebut gangguan internet terjadi hanya empat alasan karena gangguan teknis, sementara sisanya alasan politis.
Sedangkan pada 2022, terdapat kasus 36 peristiwa gangguan internet, 21 kasus terjadi di wilayah Papua. Berdasarkan penyebabnya terdapat lima tanpa keterangan, dua tanpa alasan resmi, tiga karena konflik. Sementara penyebab lainnya karena gangguan teknis dan gangguan alam.
![Infografis kasus gangguan internet di Indonesia. [Suara.com/Rochmat]](https://media.suara.com/pictures/original/2024/06/05/15263-infografis-kasus-gangguan-internet-di-indonesia.jpg)
Dimas lantas mempertanyakan implementasi dari kewenangan tersebut, khususnya mengenai tolak ukur yang akan digunakan kepolisian untuk memutus atau memperlambat jaringan internet. Tolak ukur ini juga dikhawatirkan menjadi celah penyalagunaan wewenang.
"Tentu kemudian tafsiran subjektif dari kepolisian akan mendominasi dalam melakukan bentuk-bentuk pengejawantahan dari kewenangan pengawasan dan juga pemindahan di ruang siber," ujar Dimas.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak kepolisian dalam penggunaan kewenangannya. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2023, kepolisian menempati peringkat atas institusi yang paling banyak diadukan soal pelanggaran HAM. Angkanya sebanyak 771 kasus dari 2.753 pelaporan.
Kekhawatiran penyalagunaan diutarakan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. Hal itu menurutnya karena penambahan wewenang yang tidak dibarengi sistem kontrol dan pengawasan yang kuat.
"Makanya, jauh sebelum pasal tersebut diusulkan harusnya membangun infrastruktur hukum untuk kontrol dan mengawasinya. Kontrolnya adalah KUHAP yang sekarang juga belum direvisi," kata Bambang.
Ditegaskannya kepolisian sebagai aparat penegak hukum sehingga harus bekerja berdasarkan KUHP. Kewenangan pelambatan hingga pemutusan internet harus merujuk pada undang-undang.
"Problemnya adalah dengan menyertakan pasal-pasal tersebut dalam revisi undang-undang kepolisian, bisa dibaca penambahan kewenangan kepolisian selain upaya penegakan hukum yang SOP-nya diatur dalam KUHAP," tegasnya.
Menuju Otoritarianisme
Direktur SAFEnet, Nenden Sekar Arum berpandangan, kewenangan Polri dalam draf revisi UU Polri pasal 16 huruf q itu sebagai tugas tambahan untuk melakukan penyensoran. Dia menilai hal itu akan berdampak terhadap kebebasan untuk menyampaikan pendapat di ruang digital.
"Kewenangan Polri semakin luas di ruang siber dan membuat kewenangan yang sangat tinggi untuk melakukan penindakan pembatasan hingga pemblokiran ini memperkuat gelagat otoritarianisme digital di Indonesia," ujar Nenden kepada Suara.com.
Laporan SAFEnet pada 2022, terdapat 220 juta pengguna internet di Indonesia. Data ini lantas mengkonfirmasi masyarakat sudah tidak bisa melepaskan aktivitasnya dari ruang digital.
![Infografis kasus gangguan internet di Indonesia. [Suara.com/Rochmat]](https://media.suara.com/pictures/original/2024/06/05/28515-infografis-kasus-gangguan-internet-di-indonesia.jpg)
"Padahal kita tahu internet adalah sebagai salah satu alternatif praktik ruang sipil yang seharusnya kita memberikan kebebasan bagi warga," kata Nenden.
Kewenangan ini juga dikhawatirkannya semakin membuat warga enggan melakukan kritik, karena memberikan kesan ruang digital tidak tidak lagi aman sebagai saluran kebebasan berpendapat.
"Tapi malah menjadi tempat dan target bagi represi dan juga dilimitasi bagaimana masyarakat akan jadi semakin sulit untuk melakukan praktik-praktik demokrasi melalui internet ataupun dunia digital," tegasnya.
Masih merujuk pada data SAFEnet, sepanjang 2022 terdapat 97 kasus kriminalisasi di ruang siber dengan 107 orang terlapor. Adapun latar belakang korban kriminalisasi di antaranya 32 orang merupakan warganet, influencer dan pembuat konten 19 orang, aktivis 16 orang, 11 mahasiswa.
Pemantauan SAFEnet, dasar hukum yang digunakan untuk melakukan kriminalisasi Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik serta pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian. Kemudian juga dilapisi dengan pasal 310 KUHP lama terkait pencemaran nama dan Pasal 14-15 UU No.1 1946 tentang berita bohong.
Angka korban kriminalisasi itu, mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, seperti pada 2013 hanya 20 terlapor, kemudian melonjak pada 2016 menjadi 83 terlapor. Sempat menurun pada 2019 dengan 24 kasus, namun meningkat jauh pada 2022.
Fokus Reformasi Polri
Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andi Muhammad Rizaldi menilai dibanding memperluas kewenangan Polri, seharusnya DPR merumuskan pasal-pasal yang dapat melakukan perbaikan di korps Bhayangkara.
"Lebih baik pemerintah melakukan reformasi kepolisian secara menyeluruh dengan menyentuh akar persoalan mulai dari kultur hingga institusional. Sebab selama ini kami menemukan berbagai masalah di lapangan yang melibatkan anggota kepolisian," kata Andi kepada Suara.com.
KontraS menghimpun praktik kekerasan yang melibatkan kepolisian sepanjang 2020 hingga 2024. Pada Juni 2020-Juli 2021 terdapat 651 kasus. Juli 2021-Juni 2022 677 kasus. Juli 2022 - Juni 2023 mencapai 622 kasus. Sementara Januari-April 2024 terdapat 198 kasus.
Kategori kekerasannya beragam, penembakan, penganiayaan, penyiksaan (torture), penangkapan sewenang-wenang (arbitrary arrest), pembubaran paksa, tindakan tidak manusiawi, penculikan, pembunuhan, penembakan gas air mata, water cannon, salah tangkap,intimidasi, bentrokan, kejahatan seksual, kriminalitas, hingga extrajudicial killing.
"Reformasi penting dilakukan dengan segera agar menghadirkan institusi kepolisian yang profesional, akuntabel dan transparan serta menghormati hak asasi manusia," tegas Andi.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian mengecam Rancangan Undang-Undang Kepolisian alias RUU Polri.

Ahmad Dhani berencana menyekolahkan asistennya ke Akademi Kepolisian atau Akpol.

Chaowalit Thongduang merupakan narapidana Thailand, Ia menjalani hukuman karena percobaan pembunuhan dan tuntutan pidana lainnya.
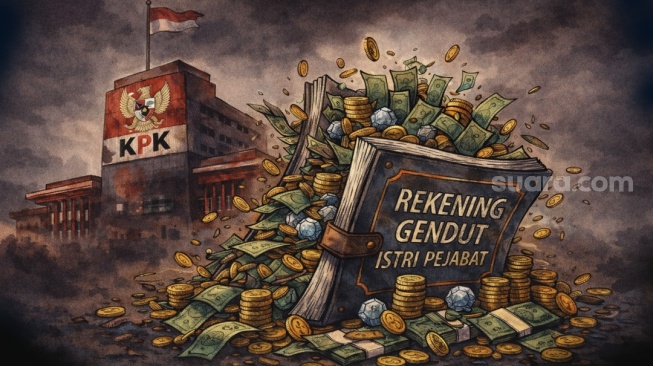
MAKI membongkar dugaan rekening gendut Rp32 miliar milik istri pejabat Kemenag yang hanya seorang ibu rumah tangga
 nonfiksi
nonfiksi
Bukan berarti tidak ramai. Lalu lalang kendaraan masih melintas di antara trem yang melaju di tengah jalan.
 polemik
polemik
Niat hati mengambil kembali tas istri yang dirampas jambret, Hogi justru ditetapkan jadi tersangka, tapi polisi memiliki alasan kuat
 polemik
polemik
Luapan sungai-sungai utama seperti Kali Angke, Krukut dan Ciliwung tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga melumpuhkan mobilitas warga
 polemik
polemik
KPK ungkap modus 'Tim Delapan' yang mematok tarif hingga Rp225 juta untuk posisi Kaur Desa
 polemik
polemik
Data mencatat, luas rendaman banjir kali ini mencapai ribuan hektare, menutup akses utama penghubung Jawa Tengah dan Jawa Timur
 polemik
polemik
Sudewo juga kurang lebih mendapatkan pesan khusus serupa dari Jokowi.