
Suara.com - Ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat di Papua dinilai banyak pihak semakin tergerus. Banyak aktivis dijerat memakai UU ITE tiap kali terlibat aksi protes. 'Pasal-pasal karet' tersebut kerap berkelindan dengan tuduhan makar, sehingga menjadi 'jaring besar' pembungkaman.
CORETAN TINTA ‘I’m Not Monkey, I’m Makar’ pada secarik kertas berukuran A5 ditunjukkannya kepada saya seusai berbincang selama 51 menit lewat sambungan telepon Jakarta – Papua. Di sudut lain dalam foto kertas yang dikirimnya lewat WhatsApp itu, tertulis 13 baris perpaduan angka dan huruf berjudul ‘Rumusan Pasal Makar’.
“Ini tulisan sa dari Rutan Polda Papua,” kata Assa Asso diimbuhi tawa.
Empat tahun lalu, pria yang akrab disapa Yally ditangkap aparat kepolisian. Sineas yang juga fotografer Papuan Voice’s tersebut dituding melakukan tindak pidana makar dan penghasutan di media sosial.
Situasi di Papua kala itu masih memanas. Ratusan mahasiswa Papua eksodus dari beberapa daerah berkumpul menduduki Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen), Abepura.
Aksi demonstrasi digelar sebagai bentuk protes atas tindakan persekusi dan rasial terhadap kawan-kawan mereka di Asrama Mahasiswa Papua, Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, 16 Agustus 2019.
***
SENIN 23 September 2019, Yally tengah memacu kuda besinya ke arah asrama di Abepura, setelah mengantar temannya ke Bandara Sentani.
Laju sepeda motor Honda Mega Pro miliknya terhenti di jalan batas antara kota dan kabupaten Jayapura. Rute tersebut sudah diblokade polisi.
“Putar balik! Putar balik!” teriak polisi.
Yally menuruti perintah tersebut, “Sore kalau situasi su kondusif baru sa balik ke Abepura” pikirnya.
Namun, sesudah berputar arah, pikiran Yally membuncah. Merasa ada sejumlah orang tak dikenal membuntutinya.
Waswas, ia terus melaju hingga satu mobil Toyota Avanza berhenti mendadak mengadang jalannya di dekat Sentani.
Empat orang turun dari mobil dan langsung menodongkan pistol mengarah ke Yally. Meski tak memakai seragam, ia tahu orang-orang itu adalah polisi.
“Abang, sa ini tidak ikut terlibat di aksi,” kata Yally sambil mengangkat kedua tangan.
Keempat polisi tetap menodongkan pistol, kali ini persis ke arah kepala Yally.
“Sa dari Bandara Sentani di batas kota disuruh balik, sa balik. Sore kalau su kondusif sa akan balik ke Abepura,” Yally coba menjelaskan.
“Hei, ko diam! Nanti ko bicara di sana saja!” bentak seorang di antara polisi.
Syahdan detik selanjutnya, tanpa ba-bi-bu, Yally yang merasa tak berkutik karena sendirian, dipaksa masuk ke dalam mobil.
Ternyata, ada dua orang lain di dalam mobil tersebut. Keduanya lebih dulu ditangkap kawanan polisi sebelum Yally. Mereka memang benar ikut aksi massa hari itu.
Yally beserta dua lainnya lantas dibawa ke sebuah ruang di kantor pemerintahan sekitar jalan batas kota.
Mereka ditahan selama tiga jam. Di sana, Yally mendapat empat kali pukulan dan tendangan pada bagian kaki serta bagian belakang tubuhnya.
Sekitar pukul 14.30 WIT, Yally kembali diangkut. Kali ini dibawa ke Mako Brimob Kotaraja. Saat hendak masuk ke mobil, seorang polisi memaksanya memakai almamater Universitas Cenderawasih yang telah disiapkan.
Yally menolak memakai jaket yang disodorkan. “Abang, sa tidak terlibat dalam aksi.” Polisi mengalah.
Saat mobil yang membawanya sampai, Yally melihat sudah ada ratusan mahasiswa dikumpulkan di tengah lapangan Mako Brimob.
Sewaktu hendak turun dari mobil, polisi kembali memaksanya memakai jaket almamater Universitas Cenderawasih.
“Buka baju ko,” hardik polisi yang membawanya. Kali ini Yally mengiyakan.
Polisi tadi lantas menyuruh Yally bergabung bersama ratusan mahasiswa yang ditangkap karena menggelar aksi anti-rasisme terhadap orang asli Papua.
Dari sekian banyak orang di sana, Yally mengenali salah satunya: Pangdam Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab.
Sekitar pukul 17.30 WIT, jenderal asli Papua itu memanggil Yally.
“Nanti adik-adik sebentar pulang, tidak ditahan,” janji Herman.
Dua polisi berpakaian preman kemudian menghampiri Yally. Mereka menariknya ke ruang interogasi. Sementara ratusan mahasiswa yang ditangkap, tetap dikumpulkan di Lapangan Mako Brimob Kotaraja berdasar asal kampusnya.
“Sa tidak terlibat sama sekali dengan aksi ini,” Yally berkukuh di hadapan polisi yang menginterogasinya.
“Kalau tanggal 19 Agustus 2019 memang sa turut ikut, karena itu aksi yang damai kami lakukan.”
Penyidik tetap tidak tak mau mendengarkan penjelasannya. Yally terus dituding sebagai aktor di balik gelombang aksi demonstrasi berujung kericuhan hingga pembakaran di Kantor Gubernur Papua, 29 Agustus 2019.
Karena tak ada pengacara atau pendamping hukum, Yally akhirnya hanya diam serta mengikuti apa kata polisi.
Setelah delapan jam diinterogasi, Yally bersama tujuh mahasiswa diangkut menggunakan mobil tahanan dalam kondisi tangan diborgol.
Pukul 02.30 WIT mereka tiba Polda Papua. Mereka disuruh tidur dalam satu ruangan penyidik. Tapi tangan Yally dan yang lain diikat ke kursi. Hari itu mereka lalui tanpa diberi makan sekali pun.
![Assa Asso, sineas sekaligus fotografer Papuan Voice’s, saat dalam tahanan polisi. [dokumentasi pribadi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/23/82809-assa-asso-aktivis-papua-1.jpg)
Nasi basi dan insang ikan
SENIN, 24 September 2019 pukul 09.00 WIT, tiga penyidik Polda Papua melanjutkan kembali pemeriksaan terhadap Yally. Pemeriksaan berlangsung selama 15 jam 30 menit, yakni hingga pukul 24.30 WIT.
“Ko orang KNPB (Komite Nasional Papua Barat)?”
Yally juga disodorkan sejumlah nama yang menurut penyidik, terlibat dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Papua. Selama interogasi, Yally tetap tak dibolehkan meminta pengacara.
Seusai diperiksa, Yally dibawa ke sel Rutan Polda Papua. Ia dimasukkan ke dalam ruangan berukuran 3x5 meter bersama 13 tahanan lain. Kondisi sel sempit membuat para tahan tidur dalam kondisi duduk, terkadang berdiri.
Hari itu, Yally akhirnya diberi makan oleh polisi. Namun, makanan yang dikasih hanya nasi basi dicampur insang ikan.
Selang sehari, Rabu 25 September, penyidik meminta akses terhadap akun media sosial milik Yally, baik Facebook, Instagram, Twitter, hingga WahatsApp.
“Silakan periksa saja. Karena HP di tangan abang dorang,” ucap Yally.
Yally baru diperiksa dengan didampingi pengacara pada Kamis, 26 September 2019. Namun, penyidik kadung menerapkan 13 pasal kepadanya.
Ketigabelas pasal itu di antaranya ialah Pasal 106, Pasal 87, Pasal 110, dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP. Selanjutnya Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 66 UU No 24/2009.
Yally juga masih harus menanggung tuduhan Pasal 160, Pasal 187, Pasal 365, dan Pasal 170 KUHP. Belum cukup, ia lantas dikenakan Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 64 KUHP, Pasal 29 KUHP.
Kesemua pasal itu memaktubkan adanya tuduhan penghasutan, perusakan, pemalangan, pembawaan alat tajam, dan makar.
Salah satu barang bukti yang dijadikan dasar penyidik adalah unggahan status di Facebook. Yally sempat menulis status “Besok wajib libur diri dan lumpuhkan kota para kapital & klonialism endonehsa. Jika Anda merasa diri martabat direndahkan, kau adalah sesungguhnya ciptaan yang mulia dan sempurna.”
Tapi, Yally berkukuh tidak terlibat dalam aksi 29 Agustus 2019. “Karena sa itu lagi di Papua Nugini.”
Wajib Makar
SELANG setahun, kejanggalan yang dirasakan Yally soal proses hukum terhadap dirinya kembali terjadi.
Jumat 3 Juli 2020, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Maria Magdalena Sitanggang memutuskan Yally tidak terbukti melakukan tindak pidana makar.
Tapi, Yally tetap dijatuhi vonis 10 bulan penjara justru karena dianggap bersalah melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.
“Di Papua ini statusnya tanah politik. Siapa pun orang Papua, entah itu bicara kemerdekaan atau tidak, aktivis atau bukan, ketika ditangkap dalam situasi seperti itu, pasal makar adalah jalan satu-satunya yang biasa mereka gunakan,” tutur Yally.
Menurutnya, polisi tak pernah mempertimbangkan konstruksi pasal terhadap orang-orang Papua yang ditangkap.
“Barang bukti yang mereka ambil itu melalui handphone. Kalau di HP sudah ada foto atau gambar bermotif Bintang Kejora, sudah masuk makar,” kritiknya.
Tak hanya itu, polisi juga tidak konsisten memakai prinsip praduga tak bersalah dalam setiap kasus politik Papua.
“Untuk orang Papua, wajib hukumnya dikenakan makar, ha-ha-ha,” seloroh Yally.
![Dokumen putusan pengadilan perkara Assa Asso. [dokumentasi pribadi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/23/54053-assa-asso-aktivis-papua-2.jpg)
Suatu ketika di Polda Papua, Yally terang-terangan menyampaikan kepada penyidik siap memberikan pendidikan terkait pemahaman tentang makar.
“Jadi sa sampaikan itu ke mereka, biasa saja. Karena sa sudah menjadi teman mereka, tinggal berbulan-bulan di tahanan Polda Papua,” ungkapnya.
Tapi tawarannya itu tak digubris, “Reaksi mereka saat itu cuma senyum-senyum saja,” kata Yally tertawa mengingatnya.
Karenanya bagi Yally, pengejaran hingga penangkapan aktivis Papua kini justru seperti tradisi yang biasa dilakukan aparat kepolisian dan TNI.
Sebab hal ini menurutnya menjadi 'ladang basah' bagi anggota Polri dan TNI untuk mengejar pangkat dan memperoleh dana berdalih pengamanan.
“Sa pikir, aktivis-aktivis Papua berkontribusi besar bagi TNI-Polri. Ketika kami ada aksi, mereka sudah dapat uang pengamanan. Sebenarnya kami yang memberikan makan kepada mereka,” ujar Yally.
Padahal menurut Yally aksi penyampaian pendapat itu dilakukan secara damai. “Tetapi ketika kami di lapangan kami berhadapan dengan polisi itu berbeda. Itu berbeda dengan di Jawa."
Pada 2018 Yally pernah aksi hari buruh di salah satu daerah Jawa. Ia menyaksikan tidak ada pengamanan yang berlebihan. Massa aksi juga bisa secara santai menyampaikan orasinya.
Sementara di Papua terjadi sebaliknya. Setiap aksi, bahkan yang digelar secara damai, TNI dan Polri serta hingga kendaraan taktis lengkap dikerahkan.
“Satu itu untuk mendapat jabatan, dan juga untuk mendapat keperluan makan minum TNI-Polri,” katanya.
“Ketika ada aksi, ada konflik yang diciptakan. Jadi bukan konflik yang sebetulnya. Biasa kami bilang pihak ketiga atau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan situasi di tanah Papua.”
Meski pernah dipenjara, tak sedikit pun Yally traumatis atau takut untuk kembali bersuara tentang isu-isu HAM dan kebebasan Papua. Ditangkap, dipenjara atau bahkan dibunuh baginya ialah risiko seorang aktivis.
Dia mengatakan, pengekangan kebebasan di tanah Papua kini melahirkan banyak solidaritas dari dalam maupun luar negeri.
Setelah gelombang pasang demonstrasi anti-rasisme, banyak pihak yang akhirnya menyadari Papua sedang tidak baik-baik saja.
“Ketika TNI-Polri melakukan pengejaran, penangkapan, pemenjaraan, pembunuhan, pemukulan, intimidasi, status perjuangan kami merasa adalah menang. Solidaritas banyak pihak juga menyadarkan kami: ‘kamu harus merdeka cepat. Kamu harus berdiri‘, begitu,” kata Yally, lagi-lagi tertawa.
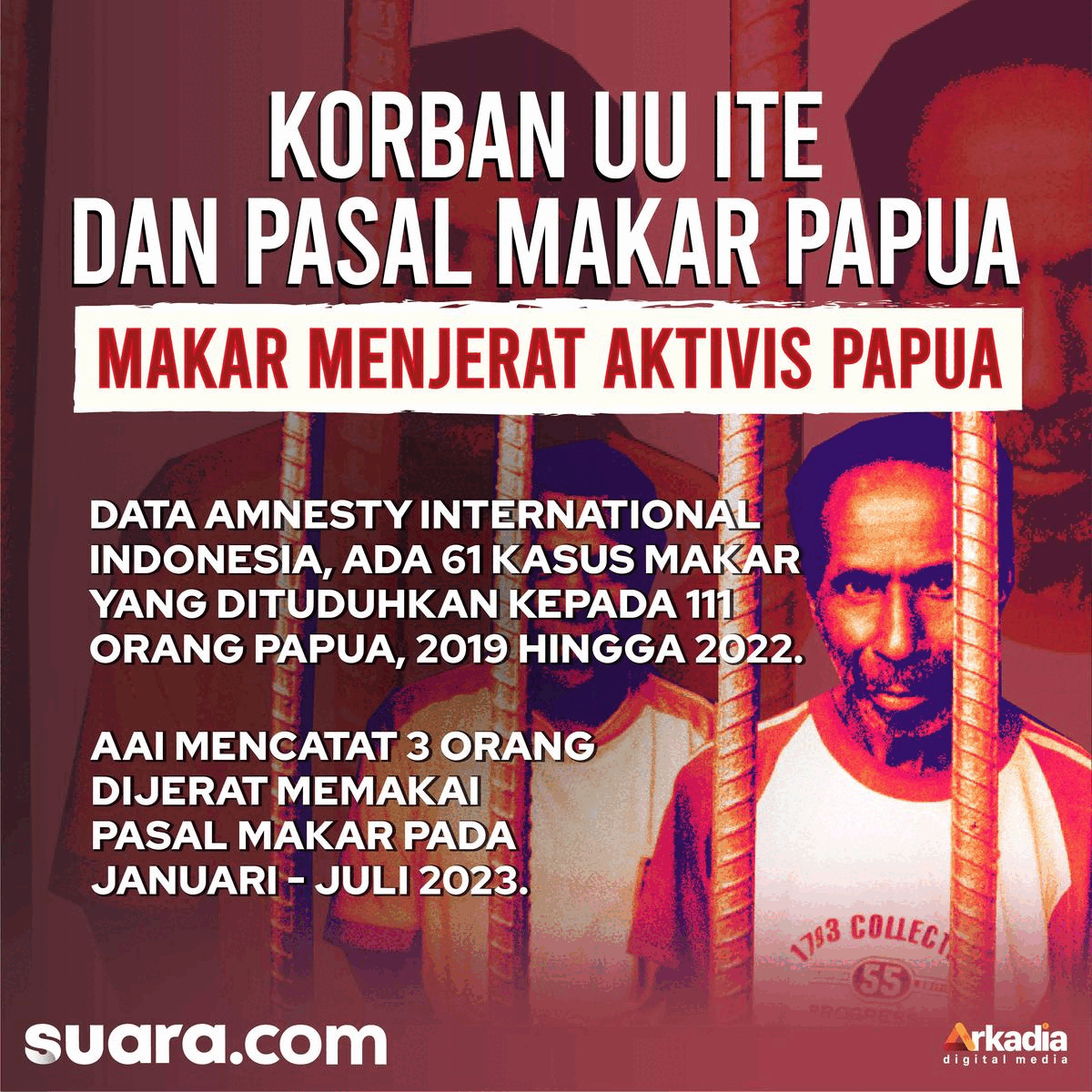
Kriminalisasi UU ITE: kesaksian korban
“SAYA kehilangan momen sewaktu anak saya lahir. Saat itu saya dipenjara,” kata Ambrosius Mulait.
Alfiora Astrella Wenearek Harhege Mulait lahir 10 Mei 2020 atau 16 hari sebelum Ambrosius Mulait dibebaskan dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat.
Tahanan politik Papua yang akrab dipanggil Ambo itu divonis sembilan bulan penjara oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Purwanto.
Ambo bersama lima kawannya yakni Surya Anta Ginting; Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni; Charles Kossay; Ariana Elopere alias Wenebita Gwijangge; dan Isay Wenda dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana makar dan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP juncto Pasal 110 KUHP.
Kesemua tuduhan dan vonis itu terkait peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi masyarakat dan mahasiswa Papua memprotes rasisme di depan Istana Negara, 28 Agustus 2019.
“Sampai hari ini juga saya belum tahu orang siapa yang bawa bendera, karena tiba-tiba bendara naik,” ungkap Ambo.
![Mantan tahanan politik Papua Ambrosius Mulait [Suara.com/Ria Rizki]](https://media.suara.com/pictures/original/2020/11/02/31071-mantan-tahanan-politik-papua-ambrosius-mulait.jpg)
***
“Dano dan Charles ditangkap, dibawa ke Polda Metro Jaya,” tulis Yumilda Kaciana alias Chika dalam grup WhatsApp bernama “Monyet se-Jakarta”, Jumat 30 Agustus 2019 malam.
Grup WA tersebut berisi mahasiswa Papua di Jakarta, sengaja dibuat untuk memudahkan koordinasi menyikapi tindakan rasialis yang terjadi terhadap kawan-kawan mereka di Asrama Mahasiswa Papua, Kalasan, Surabaya.
Setelah menyebar informasi itu, Chika dan 14 penghuni asrama Lanny Jaya di Depok, Jawa Barat menyusul suaminya Dano dan Charles ke Mapolda Metro Jaya.
Setibanya di Mapolda Metro Jaya, Chika diterima oleh Kasubdit Keamanan Negara Ajun Komisaris Besar Dwi Asih.
“Kami mau ketemu Dano dan Charles,” pinta Chika.
Dwi Asih menolak, “Tidak bisa, mereka baru bisa ditemui sesudah satu kali dua puluh empat jam.”
Chika tak mau buang-buang waktu berdebat. Mereka langsung beranjak keluar dan menunggu di trotoar depan Mapolda Metro Jaya.
Seorang polisi berpakaian preman sempat menghampiri, meminta Chika dan rekan-rekannya pulang. Bahkan, polisi itu mengakui bersedia menanggung biaya taksi untuk pulang.
“Pulang saja, kamu kan cewek, kasihan begini.”
“Yang ditahan itu suami saya. Masak saya pulang sebelum lihat dia,” sanggah Cika.
Tak lama, datang bus kota mendekat ke trotoar. Puluhan mahasiswa Papua turun menghampiri Chika. Mereka datang menyusul setelah mengetahui kabar dari grup WhatsApp ‘Monyet se-Jakarta’ perihal penangkapan Dano – Charles.
Puluhan mahasiswa Papua itu tidur di trotoar depan Mapolda Metro Jaya hingga pukul 05.00 WIB subuh. Sekitar pukul 15.00 WIB, Chika dan rekan-rekannya memutuskan untuk pulang, beristirahat, karena semalaman ada yang tak tidur dan makan.

Tiba-tiba, ada salah satu aparat kepolisian meminta lima orang perwakilan untuk masuk ke dalam Mapolda Metro Jaya guna bernegosiasi. Chika dan kawan-kawan menolak. Mereka menegaskan, mau masuk ke dalam kalau pengacara sudah datang.
Polisi itu balas mengatakan, komandannya meminta lima perwakilan hanya untuk bernegosiasi. Akhirnya, lima orang masuk sebagai perwakilan dari mereka; Isay Wenda, Ambrosius Mulait, Musa Mabel, Sehi Hillapok, dan Felis dari KontraS.
“Ini Ambros ya? Kamu Isay?” tanya penyidik menunjuk Ambo dan Isay.
“Sudah, yang lain keluar.”
Penyidik memperlihatkan surat dan langsung menangkapnya.
“Jadi statusnya saya dan Isay sudah tersangka. Pasal 106 makar juncto 110 KUHP,” ungkap Ambo mengingat kejadian sore itu.
Negara mungkin berpikir setelah menangkap dan melabelinya dengan status penjahat ‘politik’ akan menghentikan aktivisme Ambo dalam memperjuangan hak-hak kebebasan orang Papua. Tapi kenyataannya tidak.
“Setelah ada penangkapan yang lainnya itu saya pikir justru saya tambah jadi berani untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di Papua,” jelas Ambo.
Negara menurutnya melakukan cara-cara itu untuk membungkam kritik atas ketidakadilan yang terjadi di Papua.
Tak hanya kepada orang asli Papua, tapi juga terjadi kepada orang luar. Contohnya, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty aktivis HAM yang vokal mengkritisi kebijakan pemerintah di Papua.
“Jadi memang upaya negara ini secara sistematis dilakukan di Papua,” kata Ambo.
Haris dan Fatia ditetapkan sebagai tersangka karena tudingan melakukan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Mereka didakwa dengan Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 310 KUHP.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jaksa mengungkap pernyataan yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong itu berkaitan dengan konten video di akun YouTube milik Haris berjudul ‘Ada lord Luhut di bali relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’.
Dalam video tersebut Haris dan Fatia membahas kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia bertajuk ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.
“Kasus Haris dan Fatia salah satunya itu pola negara kriminalisisi. Selama ini kan negara mengkriminalisasi teman-teman aktivis Papua dengan UU ITE, ini massif sekali,” ucap Ambo.
![Anindya Shabrina Prasetiyo. [Jaring.id]](https://media.suara.com/pictures/original/2023/08/23/82589-anindya-shabrina-prasetiyo.jpg)
***
JUMAT, 6 Juli 2018 pukul 18.00 WIB, Anindya Shabrina Prasetiyo alias Anin—aktivis Front Mahasiswa Nasional (FMN)—hadir memenuhi undangan diskusi film ‘Biak Berdarah’ di Asrama Mahasiswa Papua, Kalasan, Surabaya, Jawa Timur.
Tiba-tiba pukul 20.30 WIB, TNI Polri dan Satpol PP menggeruduk dengan dalih melaksanakan operasi yustisi terhadap pendatang dari luar Surabaya.
Anin didampingi temannya Isabella dan perwakilan dari Mahasiswa Papua serta LBH Surabaya, menanyakan surat perintah atau tugas. Camat Tambaksari yang turut hadir saat itu tidak bisa menunjukkan.
Tatakala masih berdebat, seorang anggota polisi meneriaki Anin dengan kata-kata kasar. Lalu menyeret Isabella dan Soleh—pengacara publik dari LBH Surabaya. Anin ikut diseret. Ia berteriak ketika merasa dadanya diremas oleh anggota polisi.
“Silakan Anda pukul saya. Tapi jangan lecehkan saya kayak gini!” ucap Anin.
Situasi di Asrama Mahasiswa Papua saat itu kian memanas. Ratusan anggota polisi, TNI dan Satpol PP tersebut akhirnya pergi meninggalkan lokasi sekitar pukul 23.30 WIB.
Anin kemudian menceritakan kronologi keajadian penggerudukan hingga pelecahan seksual yang dialaminya itu ke media sosial Facebook.
“Di Facebook itu saya berkawan dengan banyak teman-teman jurnalis.”
Senin 9 Juli 2018, Anin melaporkan kejadian dugaan pelecehan seksual ke Propam Polrestabes Surabaya. Laporannya tak pernah diproses. Anin justru dilaporkan balik atas tudingan melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.
Laporan pertama dilayangkan oleh seseorang yang tidak diketahuinya pada 18 Juli 2018. Dalam laporan Nomor: LP/B/658/VII/2018/JATIM/RESTABES SBY itu Anin dipersangkakan dengan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 3 UU ITE dan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.
Laporan kedua dilayangkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya IKBPS Pieter F. Rumaseb. Dalam laporan Nomor: LP/B/689/VIII/2018/JATIM/RESTABES SBY tertanggal 25 Juli 2018 Pieter mempersangkakan Anin dengan Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 UU ITE terkait pencemaran nama baik.
Pada 20 Agustus 2018 Polrestabes Surabaya kemudian meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Anin sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan.
Namun, hingga lima tahun berselang, kasus tersebut digantung. Penyidik Polrestabes Surabaya tidak menetapkan tersangka, tapi tak menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
“Saya dapat kabar malah penyidiknya sudah pindah,” ungkap Anin.
Peristiwa pelecehan seksual hingga kriminalisasi UU ITE tersebut menyisakan trauma. Beberapa bulan setelah kejadian, Anin sulit mendapat ketenangan.
Ia didiagnosis menderita gangguan stress pascatrauma (PTSD), dan disarankan menjalani hipnoterapi hingga mengonsumsi obat khusus penderita gangguan kesehatan mental.
Pelanggaran komitmen negara
AMNESTY International Indonesia atau AII mencatat setidaknya ada 61 kasus melibatkan 111 orang Papua yang didakwa memakai pasal makar sepanjang tahun 2016-2019.
Sementara awal tahun 2023—Januari hingga Juli—sudah tiga mahasiswa Papua (Ambros Fransiskus Elopere, Devio Tekege, dan Yoseph Ernesto Matuan) yang ditangkap lalu didakwa melakukan tindak pidana makar.
“Negara masih menunjukkan sikap represif atas warganya di Papua yang hanya menggunakan hak mereka dalam berekspresi dan berkumpul yang dijamin di konstitusi,” ungkap Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid.
![Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid di kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2022). [Suara.com/Yosea Arga]](https://media.suara.com/pictures/original/2022/12/09/32199-direktur-amnesty-international-indonesia-usman-hamid.jpg)
Ambros, Devio, dan Yoseph ditangkap setelah menggelar mimbar bebas bersama sekelompok mahasiswa lainnya di halaman Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) pada 10 November 2022. Kegiatan yang mereka gelar secara damai ditanggapi dengan aksi kekerasan dan penangkapan oleh aparat keamanan.
“Ini artinya negara kembali menunjukkan sikap represif atas warganya di Papua yang hanya menggunakan hak mereka dalam berekspresi dan berkumpul yang dijamin di konstitusi,” jelas Usman.
AII telah menyerukan kepada pihak berwenang agar mencabut atau mengamandemen Pasal 106 dan 110 KUHP. Dengan begitu, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diharapkan tidak lagi digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, di luar batas yang diizinkan hukum HAM Internasional.
“Kami memandang pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang dikenakan Pasal 106 dan 110 KUHP melampaui pembatasan yang diizinkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia,” ujar Usman.
Penetapan tersangka hingga penuntutan terhadap para aktivis Papua dengan tuduhan makar juga dinilai Usman sebagai bentuk pelanggaran terhadap komitmen negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemimpin negara untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.
Alih-alih menimbulkan efek gentar terhadap aktivisme politik mahasiswa dan aktivis Papua, penggunaan pasal makar untuk merepresi pandangan politik damai orang Papua menurut Usman justru akan menguatkan persepsi publik bahwa negara telah melakukan kesewenang-wenangan.
“Selain itu juga menegaskan kegagalan aparat keamanan negara dalam membedakan perlakuan terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi politiknya di Papua melalui ekspresi pendapat yang damai dan mereka yang mengejar tujuannya melalui penggunaan atau ancaman kekerasan,” tutur Usman.
“Amnesty International tidak mengambil posisi apa pun tentang status politik provinsi mana pun di Indonesia, termasuk seruan kemerdekaan. Namun, menurut kami, kebebasan berekspresi termasuk hak untuk secara damai mengadvokasi kemerdekaan atau solusi politik lainnya, asal tidak melontarkan hasutan dengan tujuan mendiskriminasi, memusuhi atau menyulut kekerasan,” imbuhnya.

Motif politis UU ITE di Papua
PENGGUNAAN pasal UU ITE di Papua memang tak semarak pasal makar. Namun potensi penggunaan pasal-pasal karet bermasalah tersebut sangat besar dipakai untuk membungkam ekspresi aktivis atau masyrakat Papua yang memilik pandangan berbeda dengan penguasa.
Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet, Nenden Sekar Arum mengemukakan pola penggunaan UU ITE yang terjadi di Papua dan Jawa tidak jauh berbeda.
Berdasar data, pasal-pasal dalam UU ITE memang acap kali digunakan oleh seseorang yang memiliki kuasa untuk melaporkan atau ‘mengkriminalisasi’ orang-orang yang memilik perbedaan pandangan.
“Tapi mungkin yang perlu dilihat itu motifnya. Apa sih motif atau background-nya sehingga seseorang itu dilaporkan dengan UU ITE,” ujar Nenden.
Motif penggunaa UU ITE di Jawa berdasar data SAFEnet menurut Nenden jauh lebih beragaman. Mulai dari persoalan ibu rumah tangga hingga yang berkaitan dengan aktivisme.
“Sedangkan kalau di Papua sendiri kalaupun kita lihat biasanya memang sangat politis. Jadi karena perbedaan pandangan politiknya lah kemudian dia sangat rentan dilaporkan dengan UU ITE atau pasal makar atau pasal-pasal lain yang berpotensi untuk mengkriminalisasi ekspresi,” ungkap Nenden.
“Sedangkan kalau di Jawa jadi lebih beragam. Mulai dari nagih utang sampai perbedaan opini atau pandangan politik pun bisa dijerat.”
Akar Masalah Papua
“AGUSTUS 2019 orang-orang Papua memprotes rasisme. Tapi pemerintah malah sebaliknya melabel para mahasiswa dan aktivis yang memperotes rasisme sebagai pelaku tindakan makar,” kata Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pendeta Benny Giay.
Sejak peristiwa 2019 itu, kata Benny, terjadi remiliterisasi besar-besaran di Papua hingga saat ini. TNI-Polri juga terus-menerus mengkapitalisasi keberadaan kelompok separatis yang dilabelkan sebagai teroris bersenjata.
“Padahal memang tahun lalu atau tahan ini ada (Alaiansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP) yang mengeluarkan laporan; termasuk TNI-Polri yang ikut memompa, menyuburkan separatisme dengan terlibat dalam jual beli senjata dan amunisi. Memang ada soal besar di situ,” tutur Benny.
Benny menyayangkan sikap pemerintah Indonesia tidak kunjung menyelesaikan empat akar masalah Papua yang telah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam dokumen Papua Road Map sejak 2009 lalu.
Keempat akar masalah Papua tersebut, pertama, stigma, marjinalisasi, dan diskriminatif terhadap Orang Asli Papua.
Kedua, kegagalan pembangunan—terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ketiga, kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Keempat, praktik impunitas yang membuat tidak adanya pertanggungjawaban hukum atas kekerasan Negara Indonesia dan pelanggaran HAM Orang Asli Papua.
“Dana otsus 20 tahun pertama sejak 2001 itu, itu kita anggap memang ada unsur kesengajaan untuk membiarkan keempat masalah yang dianggap mengganggu ini, konflik ini terus berjalan,” tutur Benny.
“TNI terus-menerus mewacanakan, membahasakan separatisme sebagai musuh yang harus diselesaikan. Padahal musuh yang bisa diselesaikan dengan menyelesaikan empat akar persolan itu, tapi ini dibiarkan,” imbuhnya.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay juga berpandangan pemerintah Indonesia semestinya bisa mengguanakan pendekatan yang sama dalam menyelesaikan persoalan di Papua seperti di Aceh atau Timor Timur.

“Negara ini harus berpikir lebih maju. Apalagi negara ini sudah berpengalaman menyelesaikan konflik politik di Aceh, konflik politik di Timor Leste. Persoalan politik di Papua ini kan sama,” ujarnya.
Penangkapan dan kriminalisasi pasal makar yang terus berulang terhadap orang Papua dan aktivis yang saat ini dilakukan aparat penegak hukum menurut Gobay justru akan memperuncing konflik yang ada. Selain juga menimbulkan citra negatif terhadap Indonesia di mata internasional.
“Pasal makar sendiri secara teori pidana itu masuk dalam kategori kejahatan politik, karena kejahatan politik maka tentunya ini ada persoalan politik yang belum terselesaikan,” jelas Gobay.
Bantah kriminalisasi
Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo mengklaim tidak ada pengaman khusus yang diberikan aparat kepolisian dalam mengamankan aksi demonstrasi di Papua.
Menurutnya pola dan skema yang digunakan sama seperti umumnya yang dilakukan jajaran Polda di luar Papua.
“Secara umum sama. Artinya kami melihat kekuatan massa. Jadi minimal itu harus sebanding kekuatannya,” kata Benny.
Adapun pelibatan aparat TNI, kata Benny, dikhususkan untuk membantu mengamankan objek-objek vital. Dalam pelaksanannya dilakukan bersama anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpam Obvit.
“Kami juga siapkan kekuatan cadangan, itu untuk mengatisipasi apabila butuh tambahan di lapangan,” katanya.
Benny mengakui pola pengamanan yang digunakan banyak mengambil pelajaran dari pengalaman aksi demonstrasi besar-besaran 2019 lalu. Salah satunya pola penyekatan terhadap titik-titik lokasi yang biasa dijadikan tempat berkumpul massa.
“Jangan sampai mereka berkumpul menjadi satu, mereka kan biasa tempat berkumpulnya di beberapa titik ya. Jadi itu disekat jangan sampai bergeser, berkumpul dengan titik-titik lainnya, menjadi kekuatan yang lebih besar,” ungkapnya.
“Kami juga patroli siber, dan kalau memang ini ditemukan yang memprovokasi ya pasti dilakukan upaya penegakan hukum.”
Namun, Benny mengklaim penegakkan hukum tersebut didasari bukti. Ia menampik adanya kriminalisasi.
“Semuanya pasti harus ada bukti-bukti ya. Kami memang benar-benar—bukan dengan upaya kekerasan, tapi penegakkan hukum,” klaimnya.
---------------------------------------------------------------------------------
Artikel ini adalah hasil kolaborasi peliputan antara Suara.com dan Jaring.id yang mendapat dukungan dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).
Tim Kolaborasi
Penanggung Jawab: Fransisca Ria Susanti (Jaring.id); Reza Gunadha (Suara.com)
Penulis: Abdus Somad (Jaring.id); Agung Sandy Lesmana dan Muhammad Yasir (Suara.com)
Penyunting: Damar Fery Ardiyan (Jaring.id); Reza Gunadha (Suara.com)
Ilustrasi: Ali (Jaring.id); Suara.com

Kebakaran belasan mobil dinas itu baru padam setelah dua unit mobil Damkar tiba di lokasi kejadian.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kemenko PMK, Andi Megantara menyatakan Muhadjir kemungkinan akan terbang ke Papua.

Pemerintah berencana mengerahkan pasukan militer TNI untuk menjaga lumbung pangan.

Menurutnya, pihaknya hanya ingin pembahasan rapat tidak disalahgunakan.

Gentengisasi, di satu sisi menjanjikan estetika dan ekonomi kerakyatan, di sisi lain terbentur masalah teknis, budaya, dan anggaran
 polemik
polemik
Pernyataan tegas Jokowi ini ditegaskan kala menanggapi isu Gibran disebut-sebut berpotensi besar jadi calon presiden (capres) 2029.
 polemik
polemik
Sebelum ditemukan meninggal, sang ibu mengaku telah menasihati YBS agar tetap rajin sekolah meski kondisi ekonomi keluarga sedang sulit
 polemik
polemik
Di hadapan ratusan kader PSI di Makassar, retorika Jokowi terdengar bak proklamasi. Tak hanya memberi motivasi, tetapi juga janji keterlibatan luar biasa dari seorang presiden
 polemik
polemik
Kabar pertemuan Prabowo dengan tokoh oposisi pertama kali diembuskan oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin
 polemik
polemik
Ada batasan tipis antara menjadi pahlawan dan pelaku kriminal di mata hukum Indonesia
 polemik
polemik
Viral es gabus dituding terbuat dari spons berbahaya, jajanan jadul ini ternyata dibuat dari tepung hunkwe yang aman dan sehat